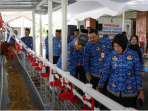damarinfo.com – Pada 17 April 1940 , pendopo Kabupaten Bodjonegoro menjadi saksi sebuah malam budaya yang tak terlupakan. Di bawah langit Hindia Belanda, tarian Serimpi — tari tradisional kebanggaan Jawa — memukau penonton dari berbagai latar belakang.
Perkumpulan wanita Wanito Mardhi Soesilo , atas prakarsa Raden Ajoe Soehono , sukses menyelenggarakan acara ini dengan dukungan kuat dari para pencinta seni dan komunitas seni dari Yogyakarta.
Saat Seni Jawa Menjadi Jembatan Budaya
Di masa kolonial yang kental dengan sekat sosial antara Eropa dan pribumi, malam itu membuktikan bahwa seni bisa melampaui pembatasan rasial dan kelas . Antusiasme masyarakat Eropa menunjukkan bahwa kesenian Jawa bukan hanya milik masyarakat lokal, tapi mulai dihargai oleh golongan penjajah.
Penyelenggaraan acara ini melibatkan kerja sama dengan dua tokoh penting dari Yogyakarta: B.R.M. Hario Soerlodiningrat , ketua sanggar Krido Bekso Wiromo, dan B.R.M. Hario Tedjokusumo , pemimpin tarian mereka. Bersama rombongan sanggar, mereka membantu panitia mendatangkan tim Serimpi berkualitas tinggi . Hasilnya? Sebuah pertunjukan yang mengundang decak kagum dari seluruh hadirin.
Tarian yang Menghipnotis Penonton
Salah satu bagian yang paling dinantikan adalah penampilan fragmen “Srikandi Larasati” , yang diambil dari lakon wayang Keraton Mataram . Suguhan ini membawa nuansa romantika yang dalam, memperlihatkan keindahan cerita rakyat Jawa yang sarat makna.
Selain itu, “Djoged Golek Mataram” dan “Gambiranom” turut menyihir penonton. Para penari mempersembahkan gerakan lemah gemulai, diiringi musik gamelan yang megah. Harmonisasi gerak dan irama menciptakan suasana magis. Banyak penonton merasa seperti menyaksikan putri-putri bangsawan Mataram hidup kembali di atas panggung.
“Seolah-olah para penari cantik yang tampak anggun itu adalah putri-putri bangsawan… diciptakan khusus untuk menari dengan penuh keanggunan dan perasaan.”
Respon Luar Biasa dari Masyarakat
Panitia menyediakan sekitar 250 kursi di dalam gedung, tapi jumlah itu ternyata tak cukup menampung antusiasme masyarakat. Ribuan orang memadati halaman kabupaten, rela berdiri demi menyaksikan setiap detik pertunjukan.
Wakil Bupati saat itu, R. Toemenggoeng A. Soeriadiningrat , juga ikut memberikan kontribusi. Ia meminjamkan gamelan barunya, “Kyai Gempjar” , yang suaranya begitu indah. Alunan gamelan itu semakin memperkaya suasana malam budaya yang penuh makna.
Warisan Budaya yang Tak Lagi Bergema
Malam itu bukan hanya hiburan biasa. Ini adalah momen ketika seni berhasil membangun jembatan antar sesama manusia , menghubungkan hati dari berbagai lapisan masyarakat.
Sayangnya, malam budaya semacam ini sudah tidak pernah lagi terlihat di pendopo Bojonegoro . Padahal, inilah saat yang tepat untuk kembali menggelar pertunjukan seni tradisional sebagai upaya mengingatkan masyarakat akan jati diri dan warisan budaya leluhur mereka.
Melalui perhelatan seni seperti ini, kita tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya, tapi juga merekat kembali rasa memiliki terhadap tanah kelahiran. Sudah saatnya Bojonegoro kembali menyelenggarakan malam budaya , sebagai bentuk apresiasi terhadap masa lalu dan inspirasi bagi masa depan.
Penulis : Syafik
Sumber : (De Indische courant edisi 17-4-1940, diunduh dari delpher.nl, diterjemahkan dengan chat.qwen.ai)